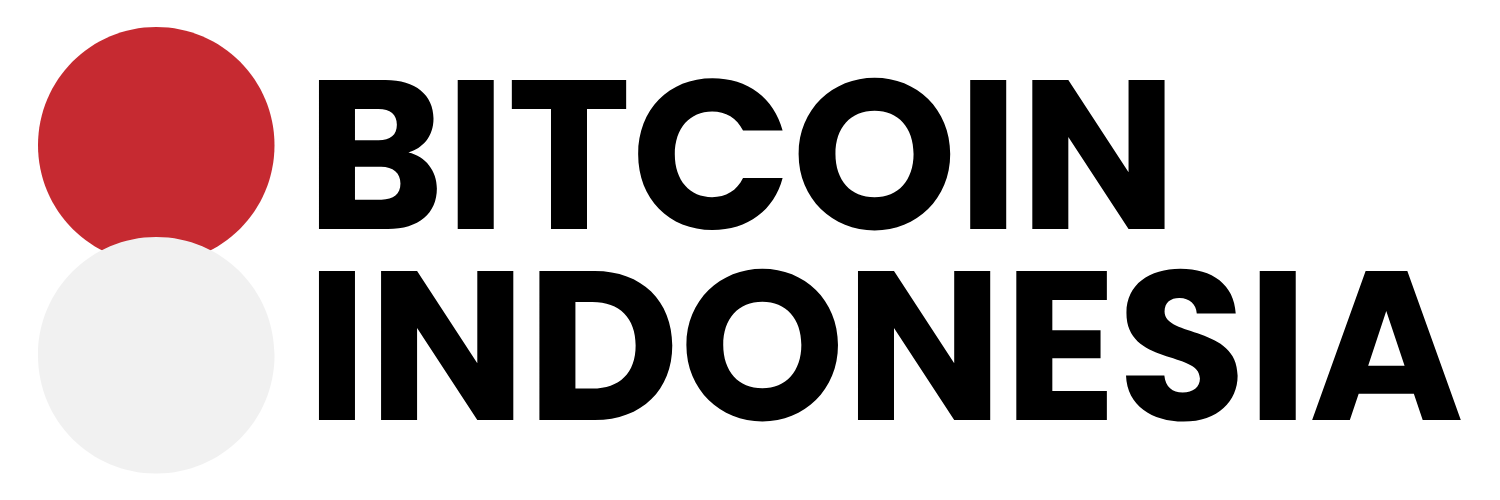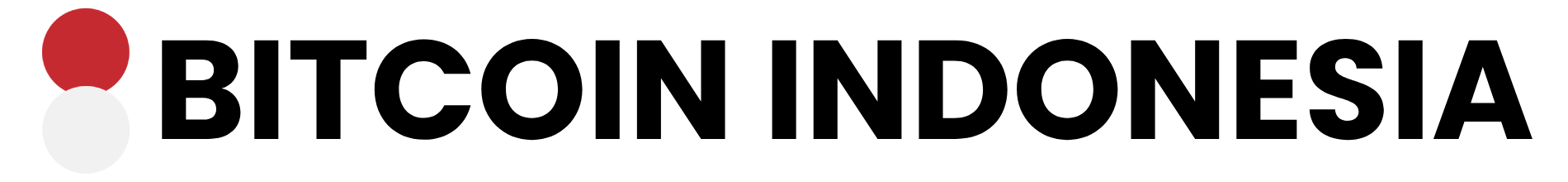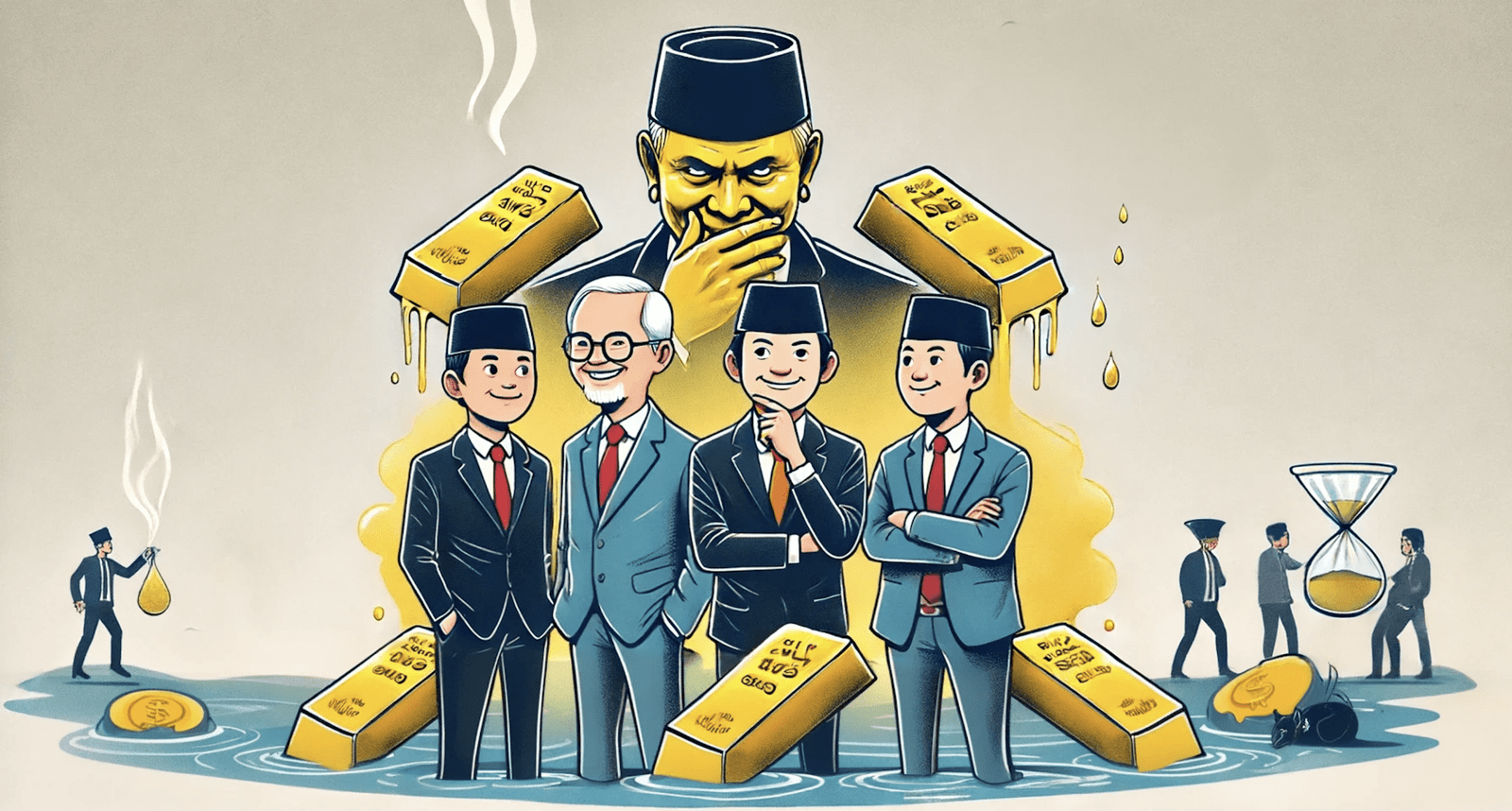Kalau dengar nama Bali, apa yang ada di kepala kalian? Di balik pesatnya pariwisata dan cafe-cafe aesthetic yang kalian pikirkan, ada biaya lain yang harus dibayar di tempat lain.
Dalam beberapa tahun saja, banyak lahan berubah menjadi deretan vila pribadi, resort, café, dan banyak fasilitas pariwisata lainnya. Sawah dan lahan hijau lainnya yang dulu menyerap air kini tertutup beton. Yang dulunya menertawakan Jakarta karena macet, sekarang macet itu jadi sahabat warga Bali.
—
Magnet Pariwisata dan Ledakan Properti
Pariwisata memang jadi “mesin uang” terbesar Bali. Membuka banyak lapangan kerja, mendatangkan devisa, dan menghidupkan ekonomi pulau.
Ada gula, ada semut. Pariwisata Bali adalah gulanya. Wisatawan lokal/asing, pekerja dari luar pulau dan pemodal adalah semutnya.
Banyak pendatang memilih menetap. Populasi bertambah, kebutuhan akomodasi melonjak, menciptakan pasar properti yang semakin besar. Kondisi ini melahirkan tren baru: lahan hijau lebih profit jika dijadikan vila atau dikavling. Pemilik lahan pun “dipaksa” oleh logika pasar: keuntungan jauh lebih besar dibandingkan mengelola lahan.
Keuntungan instan itu menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang mahal: sampah, banjir, macet dan harga tanah yang melambung tinggi.
—
Lagi-Lagi Masalah Ekonomi

Alih fungsi lahan pertanian di Bali jadi proyek pariwisata dan vila mewah, seringkali hanya menguntungkan investor, petani menjual tanahnya.
Kita bisa saja menyalahkan semua orang, tapi kalau kita tarik lebih luas lagi semua itu bermuara ke akar permasalahannya, yaitu UANG.
Sistem ekonomi kita mendorong orang untuk mengejar keuntungan jangka pendek, bukan keberlanjutan jangka panjang. Dalam sistem fiat, nilai uang terus tergerus inflasi (Bank Indonesia). Uang di tabungan semakin lama semakin kehilangan nilainya.
Sehingga orang butuh tempat menyimpan nilai dari inflasi. Kebanyakan orang melihat properti sebagai investasi “pelindung nilai”, aset yang harga jualnya hampir pasti naik. Mungkin kalau kalian tanya ke 10 orang tentang investasi, 8 orang akan menjawab tanah/properti.
Dalam logika ekonomi saat ini, tanah lebih bernilai bila diubah jadi aset fisik komersial ketimbang dijaga sebagai warisan leluhur atau ruang hijau. Maka, pilihan mengalihfungsikan lahan terasa rasional—meskipun dampaknya merusak tatanan hidup Bali sendiri. Ini bukan sekadar pilihan individu, melainkan konsekuensi dari sistem uang yang memaksa orang untuk mencari perlindungan dalam bentuk aset fisik.
—
Investasi Properti Tidak Relevan Lagi
Harga tanah di Bali, khususnya di kawasan wisata seperti Canggu, Ubud, Seminyak, dan Uluwatu, sudah melambung ratusan persen dalam 10–15 tahun terakhir.
Akibatnya, potensi capital gain mulai terbatas dan banyak investor baru justru masuk di puncak harga, sehingga risikonya lebih besar daripada peluangnya. Masalah lain muncul dari alih fungsi lahan. Dampaknya terasa nyata: banjir & kemacetan.
Jika kerusakan lingkungan ini terus berlanjut, nilai properti bisa turun karena Bali kehilangan daya tarik pariwisatanya. Di sisi lain, pemerintah juga semakin ketat dalam hal pajak dan perizinan (DJP Pajak).
Pandemi COVID-19 jadi bukti: ribuan vila kosong, harga sewa anjlok, dan banyak investor merugi. Mengandalkan satu sektor membuat properti sangat rentan terhadap faktor ekonomi makro.
Lebih jauh, properti termasuk aset yang sensitif terhadap suku bunga dan siklus ekonomi (Federal Reserve). Karena butuh modal besar, kebanyakan pembelian dilakukan lewat pinjaman. Saat bunga naik, cicilan membengkak, pasar melemah, dan harga pun stagnan bahkan turun.
Ray Dalio juga mengingatkan: properti adalah aset yang sangat terikat pada bunga, pajak, dan siklus ekonomi.
—
Literasi Keuangan dan Teknologi
Literasi Keuangan Masih Rendah
Menurut data OJK, tingkat literasi keuangan Indonesia baru sekitar 66,46% tahun 2025 (OJK & BPS).
Artinya, setengah dari penduduk Indonesia bahkan belum paham dasar-dasar keuangan. Mereka tahu cara menabung, tapi tidak paham inflasi. Mereka tahu membeli rumah, tapi tidak paham risiko bunga dan pajak.
Ironisnya, uang adalah hal yang setiap orang cari seumur hidup, tapi sebagian besar tidak benar-benar mengerti bagaimana uang bekerja. Akibatnya, masyarakat cenderung mengulang pola lama: simpan uang di properti, karena “katanya aman” dan “harganya pasti naik.”
—
Warisan Budaya Ekonomi
Di banyak daerah termasuk Bali, tanah bukan sekadar aset ekonomi, tapi juga simbol status sosial, warisan keluarga, dan bentuk kekayaan yang paling nyata. Maka, logis kalau properti dianggap “investasi nomor satu”—meski realitasnya sekarang sudah berubah.
Banyak orang belum mendapat edukasi tentang instrumen modern: saham, obligasi, emas digital, apalagi Bitcoin. Akses literasi finansial masih didominasi kota besar, sementara mayoritas masyarakat hanya menerima “kebijaksanaan turun-temurun”: beli tanah, harga pasti naik.
Padahal, teknologi hari ini memungkinkan siapa saja mengakses aset global hanya lewat ponsel. Dengan aplikasi, orang bisa membeli emas digital, saham, bahkan Bitcoin dengan modal ratusan ribu rupiah (Bank Indonesia – Uang Elektronik).
—
Bitcoin dan Literasi Baru
Nah, di sinilah Bitcoin punya peran besar: bukan sekadar aset digital, tapi juga alat edukasi finansial. Bitcoin memaksa orang belajar tentang inflasi, kelangkaan, dan nilai uang.
- Bitcoin mendorong orang untuk menabung jangka panjang.
- Bitcoin membuka akses ke aset global tanpa butuh broker, izin khusus, atau modal miliaran.
- Bitcoin sejalan dengan perkembangan teknologi: borderless, mobile-first, dan transparan.
Kompas mencatat bahwa lebih dari 93% Bitcoin sudah ditambang, dan jumlah totalnya hanya akan ada 21 juta selamanya. Artinya, Bitcoin adalah aset paling langka di dunia digital.
—
Bitcoin Relevan
Berbeda dengan properti, Bitcoin hadir sebagai alternatif “penyimpan nilai” yang tidak terikat lokasi, regulasi, atau inflasi.
- Jumlah terbatas: hanya 21 juta selamanya.
- Likuid & global: bisa dijual atau dipindahkan dalam hitungan menit, 24/7, ke mana saja di dunia.
- Tanpa biaya perawatan: tidak ada pajak tahunan, tidak ada renovasi, tidak ada izin usaha.
- Transparan & aman: kepemilikan tercatat di blockchain.
Kalau dulu orang Bali melihat tanah sebagai tempat menyimpan nilai, sekarang dunia punya alternatif baru: “tanah digital” bernama Bitcoin.
—
Kesimpulan
Bukan berarti properti tak berguna—tetap penting untuk tempat tinggal dan usaha. Tapi kalau tujuan utamanya hanya menyimpan nilai, Bitcoin lebih efisien, lebih likuid, dan jauh lebih selaras dengan tren global.
Masalah alih fungsi lahan Bali ujung-ujungnya memang soal sistem uang yang mendorong orang menimbun properti demi bertahan dari inflasi. Solusi bukan sekadar menghentikan pembangunan vila, tapi juga menghadirkan alternatif penyimpan nilai yang lebih sehat.
Dan di sinilah peran Bitcoin—memberi pilihan baru agar Bali tak perlu terus mengorbankan sawah dan ruang hijaunya demi keuntungan sesaat. Kalau kalian mau tahu lebih banyak lagi tentang dampak positif bitcoin, kalian bisa baca disini
—